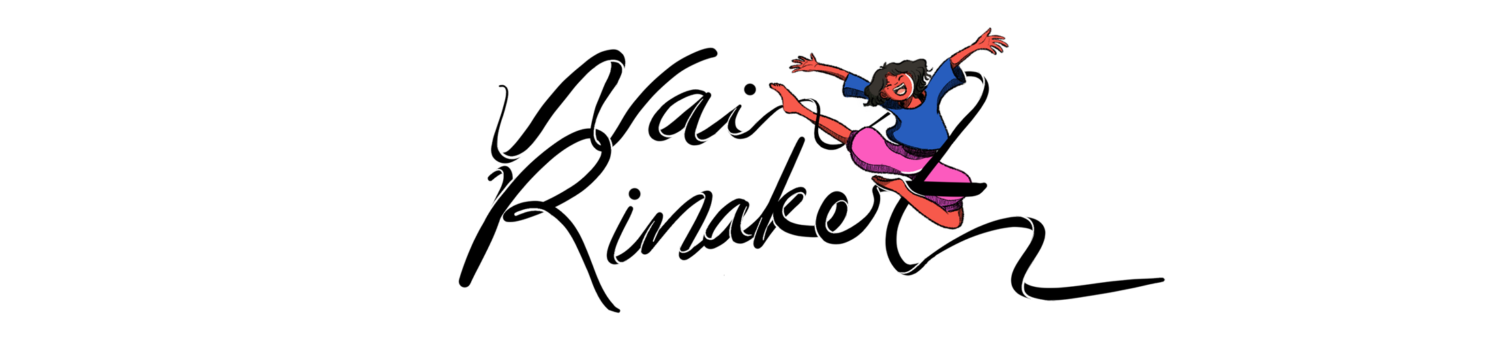Aku termangu memandang gambar yang baru saja selesai di hadapanku. Harus kujuduli apa gambar empat orang anak yang tengah berlari sambil membentangkan tangannya menirukan kepakan sayap kerumunan burung—yang, daripada tampak terusik, lebih terlihat seperti mengiringi keempatnya—di tengah padang poppy merah-putih itu?
Aku sangat jarang memberi judul pada gambar-gambarku. Mungkin ini karena gambar yang aku buat di luar proyek buku atau sampul untuk diterbitkan—dan sudah memiliki judul mereka sendiri—jauh lebih sedikit dan aku tidak berpikir mereka menginginkan nama untuk diri mereka sendiri. Kupandang lagi gambar itu lebih lama: ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki, tapi aku cukup gembira dengan hasil akhirnya.
Pertanyaan yang ingin kucari jawabannya saat mengerjakan gambar ini adalah, bagaimana cara menampilkan keramaian (padang bunga dan burung-burung) ini tanpa kehilangan perhatian pada anak-anak yang ingin kujadikan fokus? Bagaimana agar burung-burung itu terlihat memiliki gerak? Bagaimana agar, setidaknya, gestur anak-anak yang sedang berlari itu tidak tampak kaku? Bagaimana cara menyisakan ruang untuk mata memandang keluasan langit di belakang sana? Gila, apakah hal-hal teknis semacam ini masih penting untuk dipikirkan saat keadaan terasa begitu genting dan apapun yang lebih gamblang akan lebih mudah dan cepat disiarkan?
Sejenak, aku mengalihkan pandangan dari layar gambar dan tersentak menyadari di mana aku berada saat gambar itu selesai. Bunyi “bip-bip” keras yang intens masih terdengar dari layar monitor di sisi ranjang budeku. Sudah satu minggu dia terbaring di ruang ICU, berusaha bertahan hidup dengan bantuan berbagai peralatan yang menempel di tubuhnya. Ini adalah malam terakhir kami menemaninya sebelum Pae, Mae, dan adikku kembali ke Ponorogo sedang aku dan Han akan pulang ke Solo.
Pada saat kami menikmati nasi rames kantin rumah sakit yang memuaskan, bude sedang berada dalam perjuangannya sendiri dengan hidup—sekalipun kami sedang bersamanya di ruangan yang sama. Pada saat kami mendengarkan penjelasan dokter tentang kondisi bude, kehidupan orang-orang lain di berbagai dunia juga sedang berjalan menurut alur mereka sendiri, begitu juga orang-orang yang masih mengalami perang di abad ke-21 ini. Begitu pula orang-orang Palestina di Gaza, begitu pula orang-orang Papua di Indonesia.
Semua orang sedang dalam berada dalam caranya masing-masing mempertahankan hidup dan apa yang mereka yakini. Betapa dekat dan jauh jarak antara bude, keluarga kami, dan orang-orang di berbagai belahan dunia ini di hadapan ide bernama “kehidupan”. Namun, betapa “kehidupan” bisa berjalan sama sekali lain bergantung pada apa yang orang-orang miliki untuk menopangnya.
Dan aku pun sangat tahu apa yang mendorongku menggambar anak-anak di padang poppy ini: genosida terhadap orang-orang Palestina di Gaza. Tapi bukan hanya itu, melainkan kesadaran yang menyeruak pelan-pelan dan menyakitkan bahwa setelah ratusan tahun berlalu pun, bangsa-bangsa kolonialis itu tetap saja menjadi kolonialis. Kolonialisme tidak pernah terhapuskan, hanya mengalami perubahan bentuk yang kian halus dan sulit diterima sebagai salah satu bentuk penjajahan modern. Dalam berbagai aspek, kita “diminta” melihat diri kita sendiri, tanah yang kita pijak, cara kita hidup, dan cara kita memandang dunia mengikuti cara pandang mata kolonial. Dalam hal ilustrasi (buku anak) pun, ini tidak jauh berbeda.
Saat terbersit dalam benak bahwa aku harus menggambar agar kecamuk yang dibangkitkan oleh genosida yang bisa kusaksikan secara “langsung” terhadap orang-orang Palestina ini reda, aku tahu hatiku tidak hanya bersama orang-orang Palestina. Tapi juga bersama orang-orang Indonesia yang ditindas oleh bangsa sendiri, dan bersama orang-orang terjajah di berbagai belahan dunia.
Lebih daripada itu, peristiwa ini juga menohok cara pandangku selama ini sebagai ilustrator dan bagaimana aku memandang dunia melaluinya. Apakah aku akan membiarkan semua yang terjadi di sekitarku—yang dekat apalagi yang jauh—sebagai bagian yang terpisah dari proses berkesenianku atau tidak? Jawabannya terlampau jelas untukku. Aku tidak bisa mengabaikannya.
Selama ini, kurasa, aku terlampau ragu untuk bersikap secara visual. Bukan soal kata-kata yang bisa aku torehkan di atas gambar, melainkan bagaimana gambar itu sendiri bisa membawa dan menyampaikan nilai-nilai yang aku percaya? Apakah aku akan menemukan jalan menuju kebebasan visual, yang akan mampu mengantarkanku membawakan cerita-cerita dari tanahku sendiri, bukan dengan mata (visual) kolonial? Bagaimana hal itu akan mungkin kulakukan?
Kurasa, kini aku mulai sedikit mengerti. Sebuah karya yang kuat tidak lahir dari ruang hampa. Ia tidak hanya berusaha memotret sebuah peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup ekonomi, politik, atau sosial tertentu, tapi juga menangkap ide. Ide yang lahir dari pikiran-pikiran yang memiliki sikap jelas dan tegas di hadapan ketidakadilan dan penindasan, ide yang lahir dari solidaritas sebagai sesama umat manusia dan seluruh makhluk di bumi selain manusia yang mengalaminya.
Aku pun mengetik sebaris kata-kata untuk judul gambar itu: “Anak-anak Manusia.”
“Gimana perasaanmu setelah gambar ini selesai?” tanya Han.
Ada jeda sejenak sebelum aku menjawab, “Mmm… Yah, lumayan. Cukup melegakan. Tapi aku tidak tahu harus mengetikkan apa buat caption gambar ini di Instagram.”
“Mungkin memang nggak perlu kata-kata? Biarkan gambar itu menyampaikan kata-katanya sendiri.”
Aku terkesiap. “Benar juga!”
Gambar itu pun terunggah tak sampai semenit kemudian dengan tagar permintaan gencatan senjata dalam Bahasa Inggris, dengan sebuah puisi milik Ghassan Kanafani, seorang penyair dan pejuang kemerdekaan Palestina termuat di dalamnya:
“I wish children didn’t die
I wish they would be temporarily elevated
to the skies until the war ends.
Then they would return home safe,
and when their parents would ask them
Where were you?
They would say,
We were playing in the clouds.”
Esok harinya, kami pamit pada keluarga Budhe. Kami berlima berjalan kaki menuju Stasiun Gombong. Sesekali, ibuku memotret Bapak yang telah berjalan di depan dan mengajak kami berfoto di bawah langit Kebumen yang terik. Pukul 9.50, kereta Ranggajati yang kami tumpangi pun melaju menuju ke timur.
Dan hidup mesti terus berjalan.